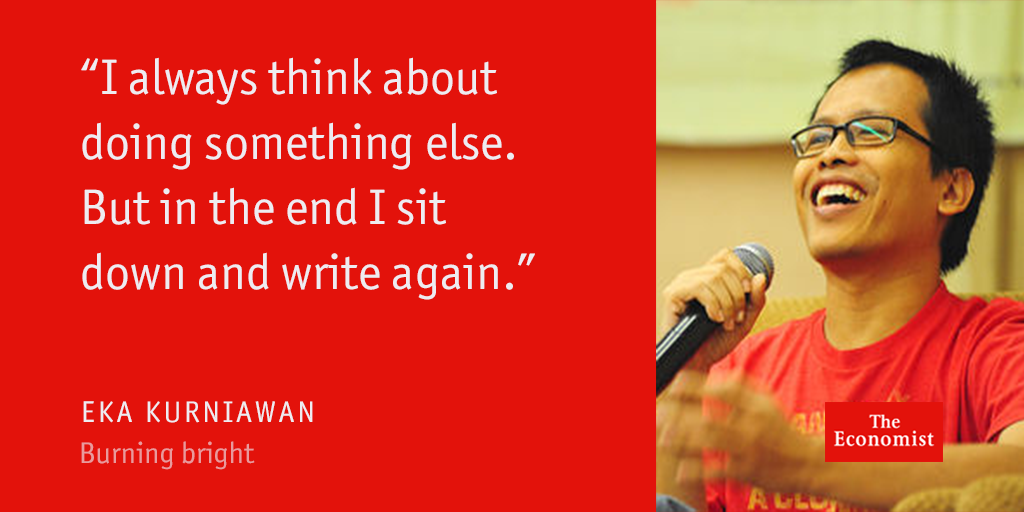Kami baru bertemu beberapa hari lalu, Rabu, untuk makan malam. Saya bahkan menyempatkan diri berfoto bersamanya, hal yang tak pernah saya lakukan selama beberapa kali bertemu dengannya. Ia makan nasi goreng seafood. Bobot tubuhnya jauh berkurang dari pertemuan terakhir kami (di tempat yang sama, di daerah Tebet). Beberapa kali ia terbatuk-batuk. Saya bahkan sudah merasa, itu akan jadi pertemuan terakhir kami. Tapi tetap tak menyangka akan secepat itu.
Saya memanggilnya Om Ben, sebab dia sendiri menyebutnya begitu sejak pertama kali kami berkenalan. Di masa Orde Baru, ia dilarang masuk ke Indonesia, membuatnya mengalihkan perhatian studi-nya ke negara-negara Asean lain, terutama Thailand dan banyak menghabiskan waktu di sana. Tahun 1999, setelah Soeharto jatuh, ia diperbolehkan untuk datang kembali. Baru beberapa tahun kemudian, 2007, seorang staf perpustakaan Cornell University (yang saya sudah beberapa kali ngobrol di forum internet) mengirim surel, bilang sang profesor akan berkunjung ke Jakarta di bulan November, dan ingin bertemu. Itulah kali pertama saya bertemu dengannya, di apartemen satu kamar di daerah Benhil, tempat saya tinggal di masa itu. Saya hanya menyuguhkan Teh Botol (untunglah dia suka), dan kami ngobrol ngalor-ngidul, terutama tentang daerah-daerah yang pernah dan ingin ia kunjungi di Jawa bagian selatan.
Ada tempat-tempat yang ia rekomendasikan untuk saya kunjungi, dan saya belum memenuhinya. Sebuah pulau di tengah situ, di daerah Tasikmalaya, yang dipenuhi ular dan kalong raksasa, misalnya. Juga kuburan seorang aulia yang ramai dikunjungi peziarah. Minatnya luar biasa, dan dia selalu penuh antusias untuk membaginya.
Ketika saya di Australia bulan Agustus lalu, saya bertemu dengan salah satu sahabatnya, Tariq Ali. Tariq bertanya satu hal yang membuat saya waswas sejak itu, “Apa yang terjadi dengan Ben?” Awalnya saya tak tahu apa maksud pertanyaan itu. Kemudian ia bergumam, “Aku kuatir. Bagaimanapun ini akan terjadi. Akan terjadi padanya, akan terjadi padaku.” Saya mulai mengerti apa yang dibicarakannya. Terutama ketika Tariq bercerita tentang keluarga Ben, yang menurutnya luar biasa. Tentu saja termasuk Perry (Anderson), salah satu editor New Left Review. Perasaan waswas saya semakin menjadi-jadi ketika bulan berikutnya saya pergi ke Amerika, dan sempat bertanya kepadanya, apakah bisa berjumpa di sana. Ia bilang tidak bisa. Dokter menyuruhnya istirahat selama sebulan. Saya merasa itu sesuatu yang serius, tapi ia menyangkalnya dengan mengatakan, kata dokter semua organ tubuhnya berfungsi dengan baik. “Aku hanya tua, harus beristirahat.” Menghormatinya, saya memutuskan tidak menemuinya.
Mungkin saya harus mengingatkan bahwa ia merupakan salah satu orang penting dalam perjalanan kepenulisan saya. Setahun sejak pertemuan pertama kali, di edisi 86 jurnal Indonesia terbitan Cornell, ia menerjemahkan “Corat-coret di Toilet”. Ia ingin pembaca bahasa Inggris membaca apa yang saya tulis. Ia melakukannya lagi dengan cerpen “Jimat Sero”, untuk jurnal Indonesia edisi 89. Ia mengaku ingin menerjemahkan novel saya, tapi tak sanggup mengingat stamina yang dibutuhkan, dan senang bisa melakukannya dengan cerpen-cerpen saya. Bahkan sebenarnya ia sempat berpikir untuk menerbitkan beberapa cerpen saya dalam satu buku. Tapi yang ia lakukan jauh dari itu. Ia memperkenalkan novel-novel saya kepada banyak orang, termasuk memberi jalan untuk saya bertemu dengan penerbit Verso Books, yang di tahun ini menerbitkan Man Tiger, terjemahan Lelaki Harimau. Ia bahkan berbaik hati menulis pengantar untuk buku tersebut. Setidaknya ia sudah melihat buku itu terbit, yang sudah ia singgung sejak perbincangan kami di tahun 2007 lalu itu.
Di pertemuan terakhir itu, ia mengaku sedang menulis otobiografi. Kita berharap bisa membacanya. Setidaknya, ada banyak orang yang bisa menceritakan kisah hidupnya, juga pergulatan intelektualnya. Di makan malam terakhir itu, saya sempat tergoda untuk membawa buku-bukunya, dalam bahasa Inggris maupun terjemahan Indonesia, untuk ditandatanganinya. Tapi di detik akhir saya mengurungkan niat tersebut, segan untuk mengganggunya. Saya hanya ingin bertemu, makan malam, dan berbincang santai. Buat saya, peninggalan Om Ben yang paling berarti tetaplah apa yang saya ingat tentangnya. Terutama segala yang pernah dilakukannya.
Selamat jalan, Om Ben.